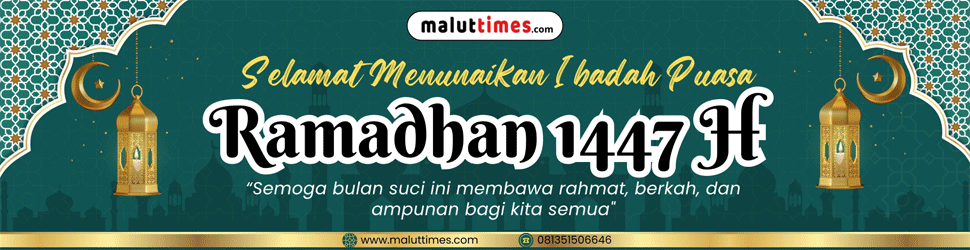Oleh: Ilham Mahmud
(Mahasiswa ilmu sejarah FIB Unkhair Ternate)
Resensi Buku: Inilah Kitab Batja Akan Tanah Minahassa Pengarang: N. Graafland Penerbit: M. Wajt dan Anakh, Rotterdam Jumlah Halaman: ±80 halaman (edisi asli) Bahasa: Melayu-Rendah Klasik Tahun Terbit: Tidak disebutkan secara eksplisit (kemungkinan abad ke-19.
Inilah Kitab Batja Akan Tanah Minahassa adalah karya penting yang menggabungkan unsur geografi, etnografi, serta nasihat moral dengan gaya naratif khas kolonial abad ke-19. Ditulis oleh N. Graafland, seorang zendeling Belanda, buku ini ditujukan bagi orang-orang Minahasa, baik tua maupun muda, untuk memperkenalkan kembali tanah asal mereka dengan pendekatan ilmiah yang populis. Menggunakan bahasa Melayu Rendah (melayu pasar), buku ini menjangkau pembaca lokal pada masanya dengan diksi sederhana namun penuh informasi.
Buku ini dimulai dengan deskripsi posisi geografis tanah Minahasa dalam konteks Hindia Belanda kala itu. Wilayah Minahasa diceritakan sebagai bagian dari Residensi Manado yang mencakup juga pulau-pulau Sangihe, Talaud, dan beberapa distrik lain. Uraian disampaikan secara sistematis, dimulai dari lokasi dan batas-batas wilayah, kondisi iklim, dan musim, hingga struktur alam seperti gunung, sungai, dan telaga. Narasi disertai dengan daftar panjang nama-nama geografis yang membentuk identitas lokal Minahasa.
Pada bagian selanjutnya, buku ini memaparkan bentuk rupa bumi Minahasa, yang didominasi oleh pegunungan dan tandjong (tanjung). Gunung-gunung seperti Lokon, Empung, Mahawu, Soputan, Kalabat, dan Duwa-Sudara disebut lengkap dengan ketinggiannya, disertai kisah rakyat atau asal-usul penamaan gunung tersebut. Di sini tampak upaya Graafland untuk memadukan pengetahuan ilmiah Barat dengan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat Minahasa.
Kelebihan utama buku ini adalah perhatian pengarang pada tatanan sosial-budaya masyarakat Minahasa.
Ia mengklasifikasikan penduduk ke dalam empat suku utama: Tou’nsea, Tou’mbulu, Toulour, dan Tou’n-Pakewa, yang masing-masing dicirikan melalui adat, bahasa, dan kebiasaan. Graafland juga mencatat keragaman bahasa, sistem pertanian seperti mapalus, serta berbagai bentuk keterampilan tradisional seperti membuat tikar, topi, dan alat-alat dari tanah liat. Meskipun ditulis dari perspektif kolonial, Graafland menampilkan kekaguman tersirat pada kecakapan masyarakat lokal.
Bagian penting lainnya adalah pembahasan tentang flora dan fauna Minahasa. Buku ini mencatat keberadaan ratusan jenis pohon, tumbuhan hutan, tanaman kebun, dan buah-buahan yang tumbuh subur berkat kondisi geografis Minahasa. Sementara itu, fauna dibahas mulai dari hewan liar seperti babi rusa dan jakki, hingga hewan piaraan seperti sapi, kuda, dan ayam. Daftar nama-nama burung dan binatang lokal disajikan dalam bahasa lokal, menunjukkan keakraban pengarang dengan lingkungan yang ia deskripsikan.
Secara keseluruhan, Inilah Kitab Batja Akan Tanah Minahassa merupakan dokumen historis dan etnografis yang sangat penting. Buku ini tidak hanya menggambarkan kekayaan alam dan budaya Minahasa, tetapi juga menjadi bagian dari upaya misionaris Belanda dalam membentuk cara pandang penduduk lokal terhadap tanah mereka sendiri. Dengan narasi yang mendidik sekaligus mengarahkan, buku ini menyimpan jejak kolonialisme yang memuji namun juga menyusupkan nilai Barat secara perlahan. Keberadaannya layak dikaji ulang dalam kajian sejarah, linguistik, maupun antropologi.
Salah satu aspek menarik dari buku ini adalah penggunaannya terhadap bahasa Melayu Rendah yang mencerminkan bahasa pergaulan zaman kolonial. Pilihan diksi dan struktur kalimat memperlihatkan kesan bahwa buku ini ditujukan bagi pembaca lokal yang sedang dikenalkan dengan sistem pengetahuan baru. Namun demikian, bahasa yang digunakan tetap cukup komunikatif, meskipun pada masa kini membacanya memerlukan adaptasi terhadap ejaan dan logika sintaksis masa lalu. Ini menunjukkan bahwa buku ini berfungsi juga sebagai instrumen edukatif kolonial yang menyentuh aspek linguistik masyarakat.
Meskipun berasal dari sudut pandang seorang zendeling (misionaris), Graafland dalam buku ini tidak semata-mata menyisipkan misi keagamaan secara langsung. Justru pendekatan yang digunakan lebih halus: ia menyampaikan bahwa agama Kristen membawa kesatuan, kedamaian, dan kemajuan. Ia membandingkan kepercayaan lokal dan kebiasaan adat dengan nilai-nilai kekristenan, dan menunjukkan bahwa konversi agama membawa perubahan sosial yang lebih baik. Dalam hal ini, buku ini menjadi cerminan strategi penyebaran agama melalui edukasi dan modernisasi.
Dari sisi struktur, buku ini disusun dalam beberapa “fatsal” atau bab yang membahas secara tematik mulai dari geografi, bentuk tanah, penduduk dan suku, pekerjaan, tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Setiap bagian disampaikan secara naratif deskriptif, kadang dilengkapi pertanyaan reflektif untuk pembaca, seakan-akan menjadi panduan membaca sekaligus berpikir. Metode penyajian ini menjadikan buku ini mirip dengan buku pelajaran atau buku populer ilmiah pada masa kolonial awal.
Kritik yang bisa diarahkan pada buku ini tentu adalah sifatnya yang sangat kolonial-sentris. Meskipun memberikan pengakuan terhadap keindahan alam dan keuletan masyarakat Minahasa, pandangan Graafland tetap berada dalam kerangka nilai-nilai Eropa: efisiensi kerja, perdagangan bebas, agama Kristen, dan organisasi sosial yang terstruktur. Hal ini tampak dari caranya menggambarkan kegiatan ekonomi rakyat yang “belum efisien” dan dorongan agar rakyat Minahasa bekerja lebih keras, lebih sistematis, dan menjual hasil kerajinan atau pertaniannya secara optimal.
Buku ini memiliki nilai historis yang sangat tinggi karena memberikan dokumentasi awal tentang bentang alam dan budaya Minahasa pada masa peralihan ke modernitas kolonial. Ia menampilkan nama-nama tempat, gunung, sungai, pulo, serta adat dan kerajinan rakyat, yang sebagian besar mungkin sudah berubah atau hilang pada masa kini. Dengan kata lain, buku ini bisa dijadikan sumber primer dalam studi sejarah lokal, geografi budaya, maupun kajian kolonialisme di wilayah Sulawesi Utara.
Secara keseluruhan, Inilah Kitab Batja Akan Tanah Minahassa adalah karya yang kompleks: ia adalah dokumen etnografis, instrumen pendidikan, dan sekaligus wacana kolonial. Nilai-nilainya bisa ditinjau secara kritis untuk memahami bagaimana pengetahuan dan kekuasaan dibentuk dalam tulisan kolonial. Bagi pembaca modern, buku ini memberi kesempatan untuk merekonstruksi ulang memori kolektif Minahasa sekaligus mengkritisi relasi kuasa dalam produksi pengetahuan tentang tanah sendiri. Buku ini bukan hanya bacaan sejarah, tetapi juga cermin dari upaya dominasi yang dibungkus dengan narasi kasih dan pengajaran. (*)